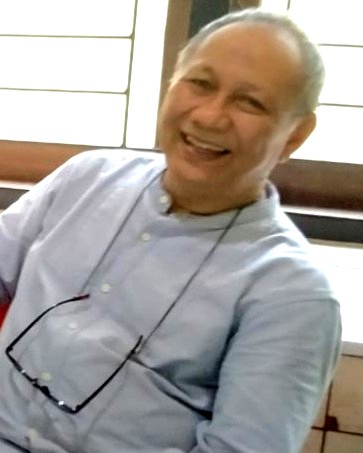“Jangan meremehkan narasi”. Begitu kata Anies Baswedan, Gubernur DKI. Ujungnya memang action. Tetapi action tanpa narasi yo go nowhere. Kalau tidak keliru pernyataan Anies Baswedan itu muncul di tengah perbincangan hangat tentang pentingnya narasi dihadapkan pada jargon “kerja-kerja-kerja”.
Gagasan memang akan berhenti hanya sampai pada gagasan jika tidak diseberangkan. Jika gagasan ingin wujud, maka gagasan itu harus diseberangkan, dikomunikasikan. Diseberangkan dengan narasi. Tentu saja bukan sekadar narasi. Diksi yang menyusun narasi itu harus sebegitu rupa sehingga gagasan yang diseberangkan gampang dipahami dan kemudian dieksekusi.
Narasi juga penting untuk branding. Baik branding produk maupun branding personal. Memang benar, narasi bukan satu-satunya unsur branding. Logo juga unsur branding. Tetapi tanpa narasi maka identifikasi, asosiasi, image (citra) dan positioning produk atau personal akan susah terbangun. Itu sebabnya dalam branding apapun logo dan jargon nyaris selalu sepaket. Jargon adalah narasi.
Begitulah, narasi akan menjadi perhatian serius bagi yang paham komunikasi. Melalui narasi, dengan diksi yang diselaraskan tentunya, citra seseorang bisa dibangun. Orang bisa merujuk teori Antonio Gramsci atau Jean Baudrillard. Gramsci dengan teori hegemoni-nya, Baudrillard dengan teori simulacra-nya. Gramsci maupun Baudrillard sama-sama mememperlihatkan bahwa kesadaran kolektif bisa dikontruksi. Gramsci umpamanya, melihat kesadaran kolektif bisa dibangun melalui intevensi bertubi-tubi idelologi, nilai, norma dan tujuan. Pada tingkat tertentu intervensi ideologi, nilai dan norma yang bertubi-tubi itu menghegemoni pikiran publik. Ujungnya, publik mengikuti ideologi, nilai dan norma yang dijejalkan terus menerus itu sebagai sesuatu yang sudah semestinya. Publik menganggapnya sebagai common sense. Ketika kesadaran kolektif terbangun dan melembaga, publik tidak bisa lagi menerima gagasan alternasi.
Bagi Gramsci mengontruksi kesadaran kolektif adalah kerja intelektual. Sebab, mengontruksi dan menghegemoni kesadaran kolektif memang bukan pekerjaan gampang. Diperlukan kerja cerdas, sistematis dan konsisten. Narasi yang dibangun lebih dari sekadar memiliki kekuatan persuasif. Narasi harus disusun sebegitu rupa sehingga juga memiliki kekuatan menyugesti, menghipnotis, bahkan menyihir pikiran obyek yang dituju. Ini kira-kira yang dimaksud Gramsci sebagai kerja intelektual.
Tidak jauh berbeda dari Gramsci, bagi Baudrillard kesadaran kolektif juga bisa dikontruksi lewat media. Narasi dan penanda (citra) didiseminasi melalui media. Perkembangan dan kemajuan teknologi sangat memungkinkan diseminasi narasi dan penanda secara masif dan konsisten. Baudrillard menyebut media dan pesan bertubi-tubi yang dikirimkannya sebagai simulacra.
Simulacra adalah wadah atau ruang di dalam mana simulasi berlangsung. Di situ narasi, gambar, penanda (citra) digelontorkan. Narasi, gambar dan penanda, karena terus menerus diterpakan, akhirnya mengaburkan batas antara simulasi dan kenyataan. Muncul kemudian apa yang Baudrillard menyebutnya sebagai hiperrealitas. Kondisi yang di dalamnya berbaur antara kepalsuan dan keaslian. Fakta berbaur dengan rekayasa.
Panjang kalau dipaparkan. intinya adalah bahwa kesadaran dan pikiran kolektif bisa dikontruksi. Realitas bisa direkayasa yang dengan rekayasa itu realitas semu bergeser dan berubah menjadi (seolah) realitas yang sesungguhnya. Maka jangan heran jika dalam kontek kandidasi dan kontestasi pilkada bermunculan narasi dan penanda (simbol dan citra) yang bertujuan mengontruksi pikiran dan kesadaran kolektif masyarakat.
Gramsci dan Baudrillard sudah mengingatkan. Gramsci mengingatkan kemungkinan munculnya upaya menggeser dan menghegemoni kesadaran kolektif. Baudrillard mengingatkan kemungkinan munculnya upaya membangun realitas buatan. Keduanya sama-sama menyiratkan kebutuhan berpikir dan bersikap kritis. Tidak menelan mentah-mentah setiap narasi dan penanda yang berseliweran di berbagai media. Juga tidak gampang terkesima pada sosok penyampai pesan. Lazimnya branding produk maupun personal memanfaatkan duta pembawa pesan (brand ambassador). Yang dipilih sebagai duta pembawa pesan pasti figur yang dianggap berpengaruh karena otoritas yang dimilikinya. Bisa otoritas intelektual, otoritas ketokohan atau otoritas lainnya yang dianggap bisa mempengaruhi, menyugesti, menghipnotis dan menyihir publik.
Pada akhirnya memang bergantung pada sikap kritis warga. Sikap kritis yang bisa membedakan realitas bikinan dari realitas yang sesungguhnya. Sikap kritis yang bisa membedakan mana kandidat yang diatribusi (dipoles) sebegitu rupa sehingga, bak orang suci, kakinya tidak menginjak tanah dan mana kandidat yang tampil utuh tanpa topeng.
Aga Suratno, Jurnalis di Jember.