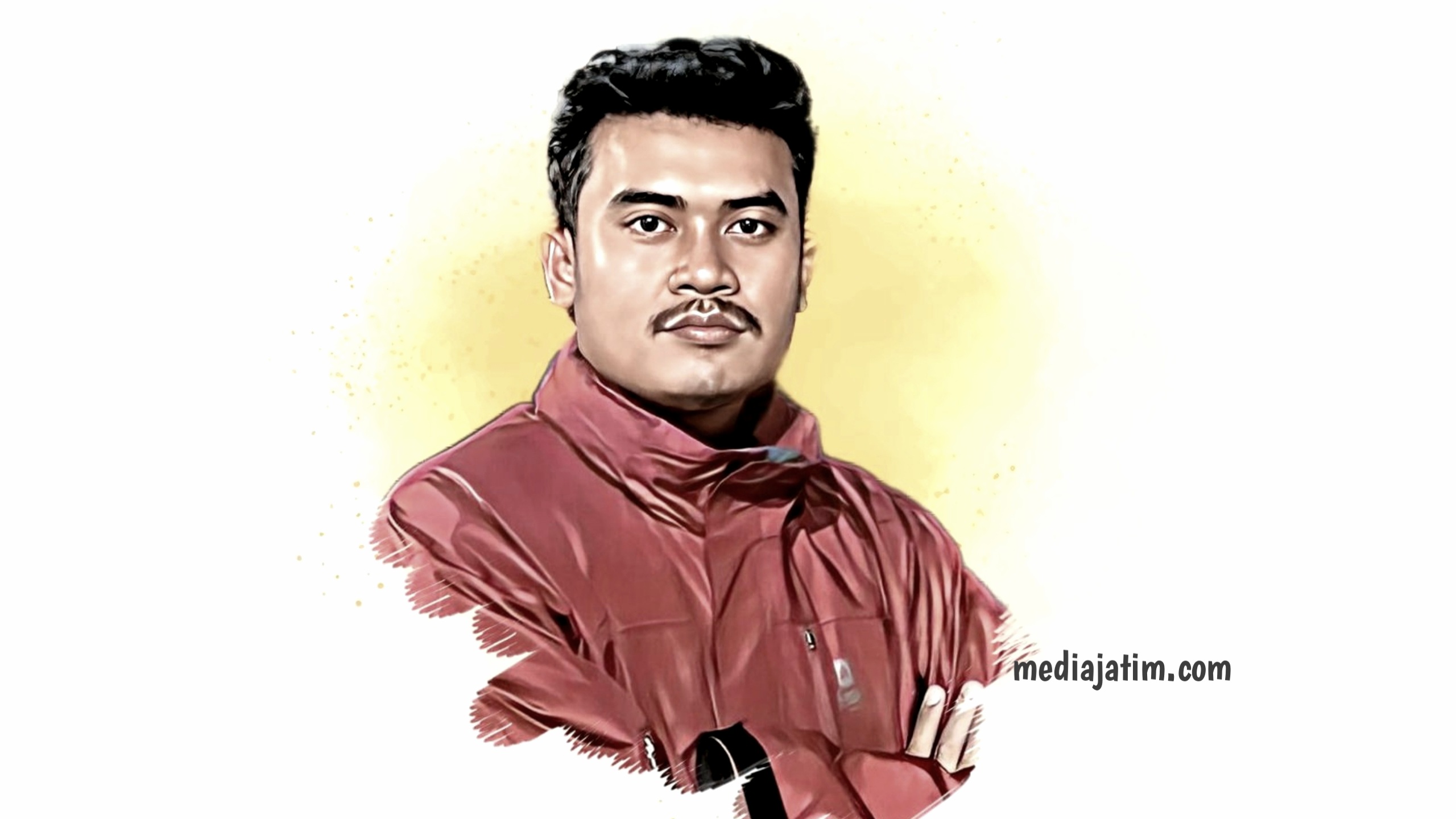Di zaman yang harus serba ramping dan ekonomis, banyak orang harus mengikat perut kencang-kencang untuk menahan keinginan dan menggantinya dengan kebutuhan.
Jika tidak benar-benar butuh, orang akan mengurungkan niat untuk belanja. Apalagi jika dasar niatnya hanya sekadar ingin, bukan butuh.
Tak ayal kini banyak orang harus mengubah gaya hidup konsumtif ke efisien. Apalagi tuntutan efisiensi itu sudah dilandasi regulasi yang jelas.
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah ingin mengefisiensi anggaran besar-besaran dengan nominal fantastis, yakni Rp306,6 triliun.
Kalau menengok Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, ada 16 pos anggaran belanja kementerian/lembaga yang dipangkas.
Akibatnya, tata kelola pemerintahan berubah drastis. Terjadi banyak adaptasi kerja di berbagai sektor. Sebagian mengeluh karena belanja barang dan jasa harus dibatasi. Sementara yang lain kebingungan karena tidak bisa lagi mengadakan rapat-rapat di luar agenda wajib.
Pokoknya, presiden ingin mendidik pemerintahan di berbagai level agar ramping dan ekonomis.
Namun, sayangnya, tidak semua pejabat mau mengikuti amanat tersebut.
Dalam kasus kepala daerah, misalnya, masih ada yang tidak mengerti konsep pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efisien. Baik dari sisi anggaran maupun realisasi kerja.
Sebagai contoh, bagaimana kepala-kepala daerah di Indonesia memilih mobil pelat merah yang akan dipakai di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024, pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk pengadaan kendaraan dinas, namun implementasinya sering menyimpang.
Kendaraan Pelat merah mewah masih menjadi simbol status, bukan alat bantu kerja. Dalam lanskap semacam ini, langkah yang dilakukan Bupati Jember Muhammad Fawait, misalnya, menjadi anomali.
Pada Senin malam, 17 Maret 2025, di hadapan awak media, dia menegaskan menolak anggaran Rp600 juta untuk mobil dinas baru dan mengalihkannya ke perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta penyediaan fasilitas bagi kaum disabilitas.
Sikap tersebut memang bukan langkah besar dalam perubahan sistem, tetapi lebih dari cukup untuk mengusik nurani politik.
Di saat yang sama, di daerah lain, mobil pelat merah tetap menjadi komoditas prestise.
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, misalnya, memilih Toyota Vellfire VIP Hybrid seharga Rp1,8 miliar sebagai kendaraan dinasnya–wabupnya, Sukriyanto memakai Hyundai Palisade XRT Rp1,2 miliar.
Di antara keduanya, ada pertanyaan yang mengganjal: untuk siapa sebenarnya kendaraan pelat merah itu ditujukan? Untuk pejabat atau untuk pelayanan publik?
Sikap Bupati Fawait barangkali akan segera dilupakan, tenggelam dan diganti dengan sikap politik lain.
Namun, di tengah derasnya desakan efisiensi anggaran, dia menjadi pengingat: bahwa di balik angka-angka dalam APBD, ada kehidupan yang bisa diubah, dan ada keputusan politik pribadi yang bisa digeser untuk publik.
Amerika dan Indonesia: Efisiensi Mobil Dinas
Di Amerika Serikat, setiap pembelian kendaraan dinas untuk pejabat pemerintah harus melewati General Services Administration (GSA), badan yang mengawasi efisiensi pengeluaran publik.
Prinsipnya sederhana: setiap kendaraan harus fungsional, ekonomis, dan sesuai kebutuhan tugas. Jika tidak, ia harus dijual atau dihentikan penggunaannya.
Sementara Indonesia, dengan segala kompleksitas birokrasinya, masih bergulat dan beradaptasi dengan prinsip-prinsip belanja barang dan jasa yang efisien. Perbedaan utama antara Amerika dan Indonesia terletak pada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.
GSA di Amerika tidak hanya bertugas mengatur pengadaan, tetapi juga mengelola lelang kendaraan bekas agar tetap menghasilkan nilai ekonomis.
Setiap tahun, ribuan kendaraan dinas yang tidak lagi memenuhi standar operasional dijual kembali melalui lelang terbuka, memastikan siklus penggunaan yang berkelanjutan.
Sedangkan di Indonesia, kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan sering kali terbengkalai di garasi kantor pemerintahan, menjadi barang tak berguna yang hanya menyerap biaya pemeliharaan.
Di Negara Bagian Washington, mobil dinas pejabat tidak sekadar fasilitas, tetapi juga bagian dari kebijakan efisiensi energi.
Di sana, pemerintah mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dengan insentif tertentu. Ada pemangkasan pajak bagi kendaraan hybrid atau listrik, ada pula kebijakan pemakaian kendaraan bersama untuk pejabat setingkat tertentu.
Di Indonesia, wacana kendaraan dinas ramah lingkungan pernah muncul, tetapi lebih sering berakhir sebagai proyek mercusuar ketimbang kebijakan sistematis yang dapat terlaksana secara kontinu.
Pada titik ini, kita dapat melihat bagaimana efisiensi belanja kendaraan dinas tidak sekadar soal pemangkasan anggaran, tetapi juga perubahan paradigma pemerintahan.
Jadi, apakah kendaraan dinas hanya sekadar alat untuk bekerja, atau menjadi lambang kekuasaan?
Jawaban dari pertanyaan ini mungkin bukan hanya perkara regulasi, tetapi juga budaya politik yang membentuknya. Dan di tengah derasnya sorotan publik terhadap anggaran negara, keputusan kecil seperti yang diambil oleh Bupati Jember bisa menjadi cermin: bahwa efisiensi tidak selalu soal angka, tetapi juga tentang keberpihakan.
Mungkin, satu penolakan terhadap mobil dinas hanyalah percikan kecil dalam lautan birokrasi yang luas. Tapi siapa tahu, percikan kecil itu bisa menjadi nyala di tengah kepongahan pejabat menggunakan mobil dinas mewah.(*)
_____
*Penulis bernama Ahmad Deni Rofiqi, jurnalis mediajatim.com